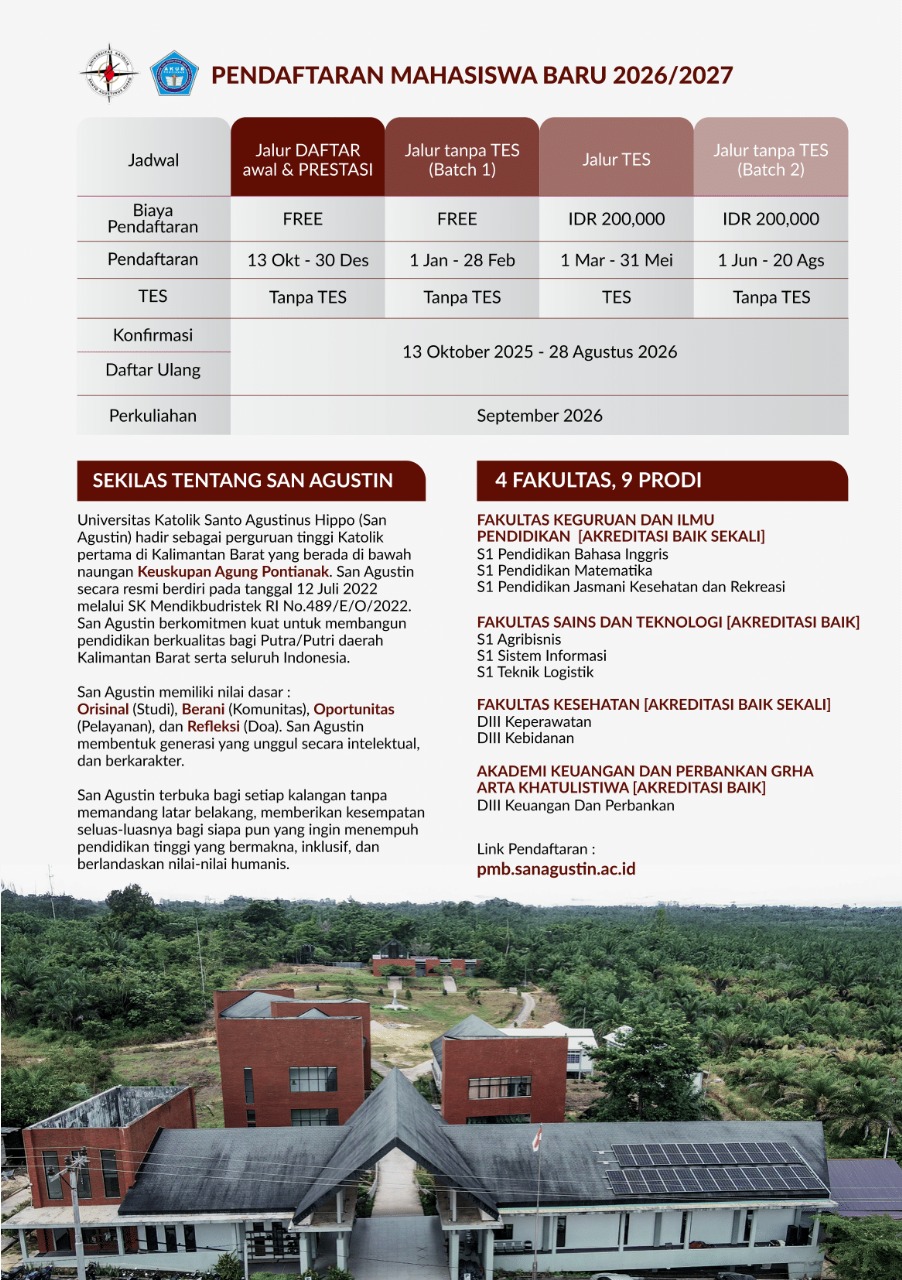MajalahDUTA.Com, Pontianak- Abraham Maslow membuat piramida kebutuhan manusia yang paling dasar, yaitu fisiologi (makan, minum). Kebutuhan dasar ini segera terpenuhi, jika tidak akan menjadi chaos bagi diri sendiri dan orang lain.
Johanes Gluba Gebze, mantan Bupati Kabupaten Merauke dalam suatu pertemuan dengan guru dan Pembina asrama mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan pertama-tama kebutuhan perut (fisiologi) dalam melaksanakan pembangunan dan pendidikan ditanah air ini.
Jika perut kita penuh semuanya aman, tetapi jika kosong itu sangat rentan ketika dilanda pandemi Coronavirus disease 2019 ( Covid-19) karena orang tidak hanya berpikir apa yang dimakan, tetapi juga ‘siapa’ yang dimakan.
Ketika ada wabah Covid-19, pemerintah kita membuat kebijakan lockdown, social distancing-physical distancing-physical distancing, stay at home, dan pembatasan social berskala besar (PSBB). Protocol ini membuat sebagian orang mulai panic dan khawatir bagaimana mendapat makanan karena pasar ditutup, roda ekoomi, transportasi dan bidang yang lain juga lumpuh. Semua aktivitas terhenti, orang hanya memikirkan dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dasar.
BACA JUGA: Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan
Presiden Joko Widodo memerintahkan semua kepala daerah agar menganggarkan bantuan kepada masyarakat dampak Covid-19. Selain itu, pihak Gereja dan relawan tergerak hati ikut membantunya.
Namun demikian, apakah bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai di tangan dampak Covid-19? Mampukah bantuan itu menjamin ketahanan pangan bagi dampak Covid-19? Pengalaman ini mengajak kita berpikir, bagaimana bangkit atas ketahanan dan kedaulatan pangan secara adil dan merata.
Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
Negeri kita ini agraris, apa betul kita kekurangan (krisis) pangan? Wabah Covid-19 dan hentinya orang beraktivitas menimbulkan kekhawatiran akan krisis pangan secara nasional bahkan global. Barangkali kekhawatiran ini berlebihan karena kita tidak sedang kekurangan-krisis pangan, tetapi krisis daya beli menurun.
Dampak terhentinya aktivitas, sebagian masyarakat kehilangan nafkah, putus hubungan kerja (PHK), dan tidak punya tabungan mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak dapat membeli makananan.
Hal ini membuat daya beli sebagian masyarakat lapisan bawah menurun. Sementara, dikalangan ekonomi menengah ke atas justru banyak makanan bahkan ada yang terbuang. Karena daya beli masyarakat bawah menurun di wabah Covid-19, ada program bantuan social (kemanusiaan) dari pemerintah, Gereja, dan organisasi relawan.
Persoalan kita bukan kekurangan-krisis pangan, dan daya beli menurun melainkan ketidakadilan pangan. Ada orang membuang makanan, sedangkan yang lain tidak mendapat (kebagian) makanan.
Paus Fransiskus mengatakan bahwa setiap kali membuang makanan, itu seolah-olah mencuri dari meja orang miskin (Laudato Si,50). Membuang makanan berarti kita melakukan tindakan ketidakadilan.
Dengan demikian, berbicara mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan mengajak kita memikirkan konsep keadilan pangan untuk semua orang. Karena ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan panggilan kemanusiaan kita.
BACA JUGA: Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan: Pilihan Pasca Covid-19
Berbicara Pangan berarti kita membicarakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak tersebut sudah diatur baik dalam pasal 27 ayat 22 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Norma hokum tersebut mendasari terbitnya UU No.7/1996 tentang Pangan.
Oleh karena itu, pangan mempunyai arti dan peran penting bagi kehidupan suatu bangsa. Jika ketersediaan pangan lebih kecil daripada kebutuhan, ekonomi suatu bangsa tidak stabil, ketahanan pangan terganggu, berbagai gejolak social dan politik dapat terjadi. Kondisi ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi secara nasional.
UU No.7/1996 itu kemudian diperbarui lagi menjadi UU No.18/2012. Dalam UU tersebut dijelaskan konsep tentang pangan, ketahanan, kedaulatan, keamanan, kemandirian, dan ketersediaan pangan.
Konsep itu diuraikan sebagai berikut. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dana tau pembuatan makanan atau minuman.
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin ha katas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untk menentukan system pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local.
BACA JUGA WEB RESMI: http://jpicbrudermtb.org/
Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi.
Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perorangan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, social, ekonomi, dan kearifan local secara bermartabat.
Ketersedian pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Konsep tentang pangan dalam UU tersebut diatas sangat bagus. Namun sangat disayangkan, kebijakan pemerintah kita belum selaras dan menyentuh konsep UU tersebut. Negara (pemerintah) hadir mengatur tanah air, untuk keadilan social dan kesejahteraan rakyat. Tanah berfungsi social dan sumber agrarian.
Tanah bukan menjadi alat menghisap manusia atas manusia lainnya. Tanah air kita tidak boleh dimonopoli oleh usaha swasta. Persoalan tanah dan air ini semakin runyam terlihat dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, percepatan reforma agraria. Jika omnibus law RUU Cipta Kerja ini ditetapkan, petani, nelayan, buruhlah menjadi korban utama bahkan kedepan semakin banyak pengangguran. Padahal, mereka garda terdepan menghasilkan pangan bagi negara dan bangsa. Kita patut mewaspadai RUU ini karena muatannya system ekonomi liberalism dan kapitalisme.
Bila mencermati kebijakan selama ini, pemerintah belum memperhatikan dan mendorong usaha tani, nelayan agar meningkatkan produksi pangan. Lahan pertanian semakin hari semakin dicaplok oleh investor atau pemilik modal (capital). Hasil-hasil pertanian dihargai sangat murah. Petani dibuat tergantung pada pupuk, pestisida kimia dan bibit unggul. Dan harganya memberatkan petani, sehingga kurang mampu membeli.
Nasib mereka termarginal yang berdampak langsung atau tidak langsung pada generasi muda kita kurang bahkan tidak tertarik di dunia pertanian. Kaum lemah ini tidak berdaya lagi mengahadap pemerintah dan hokum. Mereka selalu kalah dalam menuntut hak hidupnya (tanah-air). Pada hal kita kaya akan sumber daya alam dan manusia. Dalam kondisi ini, Yudi Latif mengajak kita berefleksi bahwa wabah Covid-19 menjadi momen penenlanjangan kesejatian kita, bahwa negeri tropis-agraris kelimpahan aneka bahan pangan tidak mampu menghasilkan kedaulatan pangan. Lautan luas tidak mampu memenuhi garam dan protein (Kompas, 20 Mei 2020).
Pandemic Covid-19 mengajari kita juga memandang ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan keamanan pangan secara lain. Kita tidak lagi melakukan eksploitasi atas alam, tetapi konservasi, sehingga sama-sama menguntungkan dan berkeadilan. Setiap kita tidak lagi bermental egologi, tetapi ekologi. Artinya ada pertobatan ekologis.
Artinya ada pertobatan ekologis, bukan hanya alam yang diselamatkan melainkan juga manusia. Jika tidak, kita akan kesulitan pangan dalam mempertahankan hidup di planet ini dan species manusia akan terancam punah (Joan Damaiko Udu, Kompas, 20 Mei 2020).
Kita harus bangkit menegakkan keadilan pangan. Padi bukanlah satu-satunya makanan pokok, sehingga harus tergantung beras impor. Kita masih punya alternative makanan pokok lain, seperti jagung, ubi, keladi, pisang, sorgum yang patut dibudidayakan sesuai dengan kearifan local.
Demi kesehatan tubuh, kita hendaknya mengurangi bahkan tidak lagi mengkonsumsi makanan instan yang sarat bahkan pengawet kimia. Kita tahu hal itu, tetapi gaya dan pola makan kita sekarang cenderung memilih bahan makanan instan yang nota bene dari impor. Kondisi ini menuntut kita kembali menata pertanian secara organic untuk mendapatkan asupan pangan yang kaya gizi, nutrisi dan bermutu tinggi.
Dengan demikian, kita dapat memberikan sumbangan berarti bagi ketahanan dan kedaulatan pangan di negeri ini. Kita bukan kekurangan-krisis dan daya beli menurun atas pangan melainkan belum mengusahakan secara maksimal, sehingga larut dalam system ekonomi global.
Agar tercapai impian dan niatan ini, kita dengan tegas menolak menjual tanah, air,untuk tambang, perkebunan berskala besar dan membatasi impor makanan. Sikap tegas ini diperlukan karena jika dibiarkan ke depan petani dan nelayan akan kehilangan lahan garapan. Petani dan nelayan didorong difasilitasi agar memaksimalkan usaha produksi (swasembada pangan), memperhatikan harga yang pantas (tinggi) bagi hasil petani-nelayan, sehingga tidak terjadi monopoli ekonomi.
Kita giatkan kembali gerakan cinta pangan local yang menjadi kearifan local kita masing-masing. Dengan jalan demikian, kita dapat membangun ketahanan dan kedaulatan pangan di negeri agraris ini. Dan kita boleh merasakan keberadilan pangan untuk memenuhi kebutuhan ‘kampung tengah.’
Penulis: Br.Gerardus Weruin, MTB