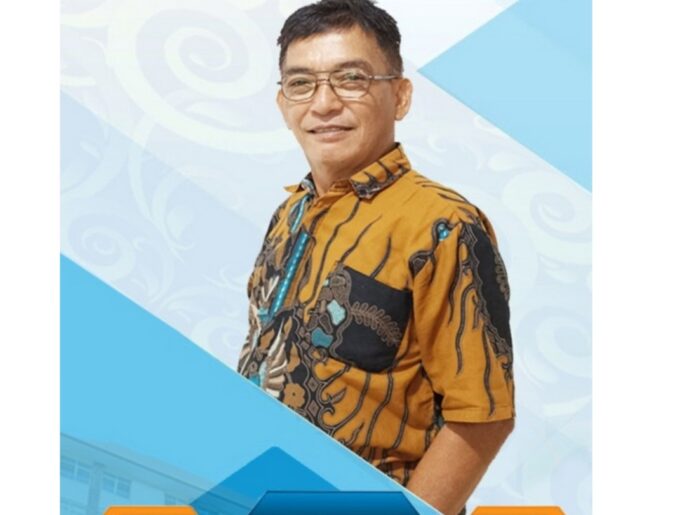Duta, Pontianak | Di tengah derasnya arus globalisasi dan ledakan teknologi komunikasi, bahasa kerap dipandang hanya sebagai alat praktis untuk menyampaikan pesan. Pandangan ini keliru. Bahasa, khususnya bahasa Indonesia, bukan sekadar medium berbicara atau menulis; ia adalah rumah kebudayaan, cermin moral, dan fondasi pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Tanpa kesadaran mendalam terhadap peran ini, kita akan menyaksikan degradasi identitas nasional yang pelan tetapi pasti.
Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Pengakuan itu kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 dan 36C yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan menuntut perlindungan hukum. Artinya, bahasa Indonesia tidak hanya memiliki nilai praktis, tetapi juga martabat konstitusional. Ia mengikat lebih dari 700 kelompok etnis dalam satu simpul identitas. Dari Aceh hingga Papua, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi yang memungkinkan kita menyebut diri sebagai bangsa, bukan sekadar kumpulan suku.
Namun, di era modern, posisi ini kian diuji. Fenomena “gengsi berbahasa asing” menjadi pemandangan sehari-hari. Di media sosial, ruang kuliah, hingga obrolan santai, campur-campur bahasa Inggris kerap dianggap keren, sementara bahasa Indonesia dipandang kuno. Generasi muda, termasuk pelajar dan mahasiswa, merasa lebih percaya diri bila menaburkan istilah asing, seolah mutu intelektual diukur dari seberapa banyak kata serapan barat yang bisa diselipkan. Di sisi lain, bahasa gaul yang lahir dari kreativitas urban juga sering jauh dari kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Gejala ini bukan sekadar perubahan selera, tetapi refleksi krisis kebanggaan terhadap jati diri.
Padahal, penguasaan bahasa Indonesia yang baik memiliki fungsi jauh lebih besar daripada sekadar gaya bicara. Bahasa yang terstruktur menuntun pikiran yang teratur. Seseorang yang mampu menulis dan berbicara secara logis biasanya juga berpikir sistematis. Dari sinilah karakter terbentuk: kesabaran untuk merangkai kalimat dengan cermat, kejujuran dalam mengekspresikan gagasan, dan kesopanan dalam memilih kata. Sebaliknya, penggunaan bahasa secara serampangan sering berbanding lurus dengan pola pikir yang semrawut.
Pakar pendidikan Mulyasa menegaskan bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai penunjang pembangunan sosial, politik, dan budaya. Ia bukan hanya sarana komunikasi, tetapi wadah ekspresi emosi, harapan, dan gagasan yang kemudian mewujud menjadi tindakan.
Artinya, penguasaan bahasa berkorelasi langsung dengan kapasitas intelektual dan emosional. Dalam konteks mahasiswa, pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi seharusnya tidak dipandang sebagai mata kuliah formalitas, melainkan proses pembentukan karakter. Melatih keterampilan menyimak menumbuhkan sikap setia dan menghargai pendapat orang lain. Membaca dengan teliti mengasah ketajaman analisis. Berbicara dan menulis dengan teratur melatih keberanian menyampaikan ide secara jernih, sekaligus mengajarkan tanggung jawab terhadap kata-kata sendiri.
Fungsi ganda bahasa Indonesia—sebagai cermin kepribadian dan alat pemersatu—membuatnya memiliki peran strategis dalam pengembangan bangsa. Pertama, bahasa adalah identitas moral. Ungkapan “bahasa menunjukkan bangsa” bukan sekadar pepatah. Ketika masyarakat terbiasa berbahasa dengan santun, teratur, dan jelas, citra bangsa pun terangkat. Kedua, bahasa Indonesia adalah perekat kebhinnekaan. Di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, ia menyediakan ruang perjumpaan yang memungkinkan kita saling memahami tanpa kehilangan akar lokal. Ketiga, bahasa adalah wahana pewarisan pengetahuan dan budaya. Melalui bahasa Indonesia, cerita rakyat, tembang, dan ilmu pengetahuan dapat diteruskan lintas generasi. Dan keempat, bahasa menumbuhkan identitas nasional: rasa bangga sekaligus kesadaran bahwa kita bagian dari sejarah bersama.
Gorys Keraf, pakar linguistik Indonesia, menambahkan dimensi penting lain: kejujuran dan kejelasan dalam berbahasa mencerminkan kejernihan berpikir. Struktur kalimat yang rapi melatih logika. Penggunaan gaya bahasa yang bervariasi menumbuhkan daya tarik dan imajinasi, menumbuhkan kepercayaan diri, bahkan kemampuan persuasif. Lebih jauh, penguasaan bahasa yang baik adalah wujud sikap kebangsaan, mengingat bahasa Indonesia sendiri lahir dari semangat persatuan.
Jika kita hubungkan seluruh pemikiran itu dengan realitas sekarang, tantangan terbesar generasi muda bukan hanya godaan untuk meninggalkan bahasa Indonesia, tetapi juga kehilangan kesadaran bahwa bahasa adalah alat pembentukan budi pekerti. Sopan santun, integritas, dan kejujuran bukan hanya diajarkan dalam mata pelajaran moral, tetapi juga ditanamkan melalui kebiasaan berbahasa. Ketika seseorang terbiasa menyusun kalimat dengan hormat dan tepat, ia belajar menghargai lawan bicara. Ketika ia berupaya menulis dengan jujur dan tidak memelintir fakta, ia melatih diri untuk berpikir etis.
Apa yang harus dilakukan? Pertama, dunia pendidikan perlu menempatkan pelajaran bahasa Indonesia sebagai penguatan karakter, bukan sekadar penguasaan tata bahasa. Pembelajaran harus kreatif: mengajak mahasiswa berdiskusi, berdebat dengan argumen yang terstruktur, dan menulis esai yang bernas.
Kedua, pemerintah dan lembaga kebudayaan mesti memperluas ruang apresiasi bahasa Indonesia di media digital—dari film, musik, hingga konten media sosial—sehingga generasi muda melihat bahasa Indonesia bukan sebagai beban, melainkan kebanggaan. Ketiga, keluarga memiliki peran tak tergantikan. Orang tua yang membiasakan komunikasi santun dan kaya kosakata di rumah memberi teladan paling awal dan paling efektif.
Kita juga perlu menanggapi realitas globalisasi secara cerdas. Menguasai bahasa asing tentu penting dalam dunia kerja dan ilmu pengetahuan. Tetapi, kebanggaan terhadap bahasa sendiri tidak boleh tergadaikan. Sikap ideal adalah dwibahasa yang sehat: piawai berbahasa asing untuk menjangkau dunia, tetapi kukuh mencintai bahasa Indonesia sebagai pijakan identitas. Sebagaimana pepatah, “Orang yang kehilangan bahasa ibunya ibarat pohon yang kehilangan akar.” Tanpa akar itu, kita akan mudah tercabut dari tanah sejarah.
Akhirnya, peran bahasa Indonesia dalam pembentukan karakter generasi muda bukan teori belaka. Ia adalah realitas yang kita alami setiap hari. Dari cara mahasiswa menulis skripsi, anak sekolah menanggapi guru, hingga percakapan santai di ruang publik, bahasa membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk watak, dan watak membentuk peradaban. Jika kita abai, peradaban itu rapuh; jika kita peduli, bahasa Indonesia akan terus menjadi pilar bangsa yang kokoh.
Di era global, identitas tidak perlu dipertentangkan dengan keterbukaan. Justru, semakin kita akrab dengan dunia, semakin penting menegaskan siapa kita. Dan salah satu cara paling nyata untuk menegaskannya adalah dengan mencintai, memelihara, dan menghidupkan bahasa Indonesia dalam tutur, tulisan, dan tindakan sehari-hari. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi; ia adalah jiwa bangsa. Menjaganya berarti menjaga diri kita sendiri.
Penulis: Drs. Suardi, M.Pd.
Penyunting: Samuel, S.E., M.M.