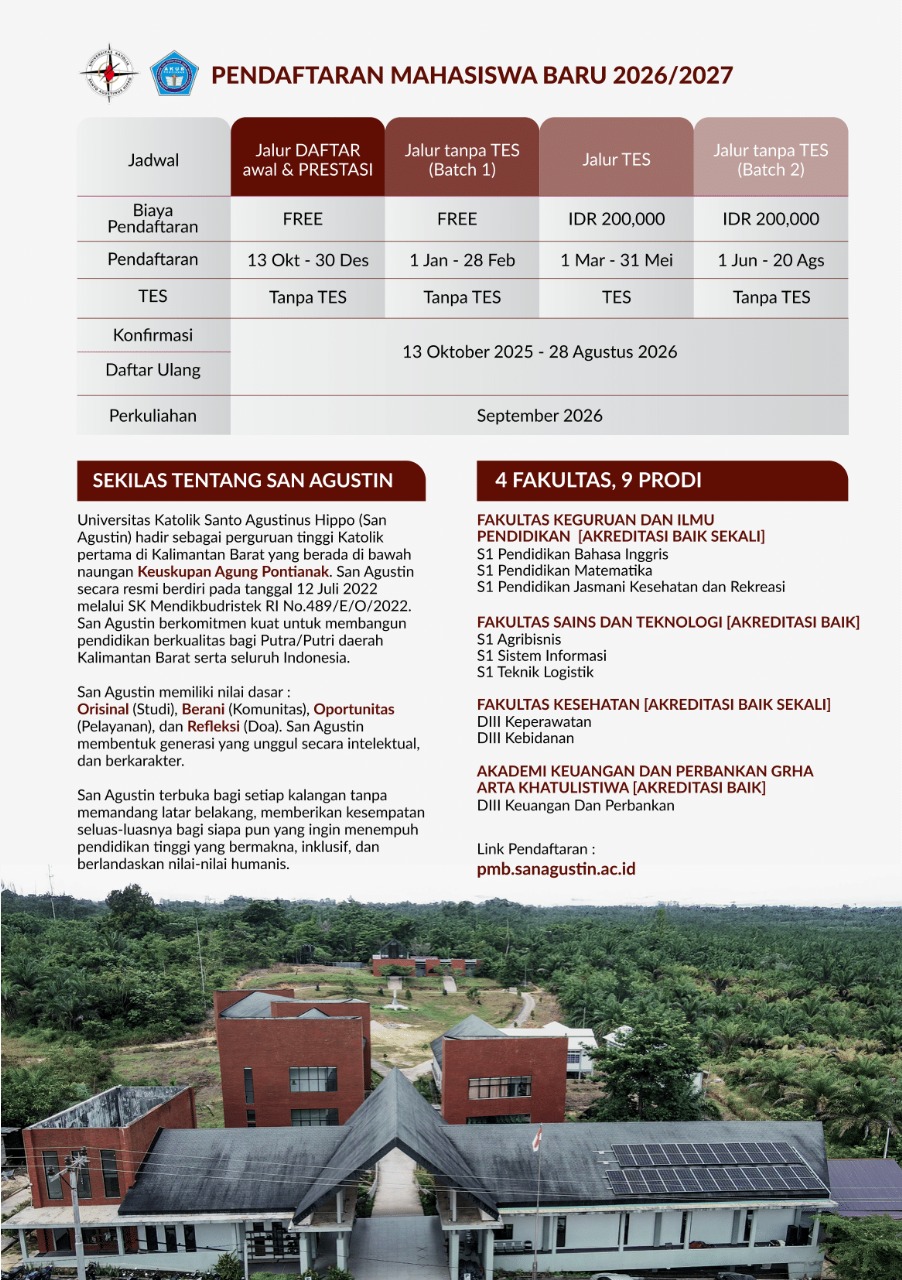MajalahDUTA.com, Sumut – MAKNA RUMAH BETANG PANJANG BAGI SUKU DAYAK SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI TENGAH ARUS MODERNISASI
Abstraksi
Rumah betang panjang merupakan rumah yang memiliki ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh suku Dayak yang ada di Kalimantan. Rumah betang panjang ini, menjadi pusat kebudayaan adat dan ritual oleh suku Dayak. Di mana rumah betang panjang ini juga masih dihuni oleh orang-orang Dayak sebagai tempat tinggal mereka dibeberapa daerah yang ada di Kalimantan, khususnya daerah yang ada di Kalimantan Barat. Walau begitu banyak rumah betang panjang yang dimiliki oleh suku Dayak, namun ciri khas yang pasti tidak akan hilang, yaitu panjang dan tinggi.Bagi orang Dayak yang bertempat tinggal di Rumah betang panjang ini memiliki makna dan fungsi sosial bagi mereka sendiri dan sesama, yaitu rasa persaudaraan dan saling tolong menolong yang kuat tetap mereka pertahankan dengan teguh. Rumah betang panjang menjadi pusat bagi orang-orang Dayak menjalankan kebudayaan dan ritualnya, karena rumah betang panjang sendiri masih dipercaya memiliki sifat yang magis bagi orang Dayak. Misalnya saja mengenai bentuk dan tangga untuk menaikinya. Hal ini dipercaya bahwa bentuk dan tangga memiliki makna spiritual yang membuat kita setelah kematian nanti bisa sampai kepada sang pencipta (Penompa).
Kata Kunci: Rumah Betang, Rumah Panjang, Bentuk Fisik, Tempat Hunian, Pusat Organisasi Sosial, Sekolah Non-Formal, Seni, Tradisi, Religius, Estetika.
Pengantar
Apabila mendengar nama rumah betang panjang, maka orientasi pikiran sebagian besar orang pasti akan langsung tertuju kepada sebuah bangunan yang tinggi, panjang, memiliki bilik-bilik dan di dalamnya ada begitu banyak orang suku Dayak dengan ciri khas tertentu. Memang gambaran rumah betang panjang kurang lebih demikian. Akan tetapi bila kita menelisik lebih jauh tentang makna dari rumah betang panjang, maka pembahasan kita tidak lagi hanya terorientasi pada bentuk fisik saja, melainkan lebih dalam dari itu, yakni sebagai salah satu simbol dan jati diri orang Dayak.
Saat ini, di beberapa tempat masih bisa dijumpai rumah betang panjang, namun keberadaan masyarakat Dayak yang masih tinggal di rumah betang panjang sudah tidak banyak lagi. Ada yang memilih untuk tinggal di rumah tunggal (membangun rumah di luar rumah betang panjang). Ada juga yang kondisi rumah betang panjang sudah sangat memprihatinkan sehingga tidak layak lagi di huni. Dan, ada juga rumah betang panjang yang sudah runtuh, rata dengan tanah akibat tidak ada perawatan. Intinya, keberadaan rumah betang panjang kini sudah mulai langka.
Makna Rumah Betang Panjang
Rumah betang panjang merupakan rangkaian tempat tinggal yang sambung-menyambung sehingga memanjang karah samping kiri dan kanan yang telah dikenal hampir oleh seluruh orang Dayak. Rumah panjang memberikan makna tersendiri bagi penghuninya. Bagi masyarakat Dayak, rumah betang panjang adalah pusat kebudayaan mereka, karena hampir seluruh kegiatanm hidup mereka berlangsung di sana.[i] Pada saat ini, banyak penilaian mengenai eksistensi rumah betang panjang yang dianggap tidak cocok dengan kehidupaan masyarakat sekarang ini. rumah betang panjang dinilai sebagai sesuatu yang menjadi penghambat kemajuan dan pembangunan.
Menurut Michael R. Dove dalam bukunya Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi, mengatakan: “dalam konteks studi dan perencanaan pembangunan di Indonesia, kesan komunalisme atas rumah betang panjang suku Dayak kadang-kadang dianggap sebagai suatu kekurangan, pada waktu tertentu sebagai keuntungan dan terkadang sebagai gabungan dari keduanya…”.[ii]
Pada tingkat pemerintahan provinsi di Indonesia, bentuk organisasi rumah betang panjang secara jelas dianggap menjadi masalah. Para pejabat provinsi mengeluhkan atas rumah panjang. Rumah betang panjang dikatakan “menjemukan, “kotor” karena masalah higiene dan sanitasi dan “berbahaya” (karena adanya ancaman penyaki dan bahaya kebakaran yang tidak disengaja). Bila dilihat terkadang kritikan ini bersifat subjektif. Karena masalah higiene, sanitasi dan kesehatan tidak lebih buruk di sebuah rumah betang panjang dibandingkan dengan sebuah desa yang terdiri dari rumah-rumah untuk kediaman satu keluarga. Api bukan menjadi ancaman besar di tengah hutan rimba Kalimantan yang banyak hujannya.[i] Hal ini menjadi tampak jelas bahwa alasan-alasan untuk menjelekkan rumah betang panjang, jelas sangat merugikan bagi kehidupan budaya komunal masyarakat Dayak.
Bentuk Fisik Rumah Betang Panjang
Proses pembangunan rumah betang panjang berbeda dengan proses pembangunan rumah pada umumnya. Pada zaman dahulu pembangunan rumah betang panjang masih menggunakan bahan-bahan yang sangat tradisional, mulai dari kayu sebagai bahan utama, pasak untuk mengkaitkan tiap-tiap kayu (sebagai pengganti paku) dan atap masih menggunakan anyaman daun enau atau sirap (atap dari kepingan kayu belian).[i] Namun bila kita melihat pembangunan rumah betang panjang pada zaman ini, maka kita bisa melihat hampir seluruh konstruksi bangunan menggunakan beton dan bahan modern lainnya. Selain itu juga, bila dahulu pengerjaan pembangunan rumah betang panjang bisa memakan waktu yang lama, maka kini pembangunan itu bisa lebih singkat karena didukung oleh alat-alat bangunan yang canggih.
Namun demikian, apabila melihat bentuk fisik bangunan rumah betang panjang, baik itu tradisional, maupun modern, kita akan menemukan banyak kesamaan. Hal ini dikarenakan sejak awal pembangunan rumah betang panjang (tradisional), hingga modern seperti sekarang ini, bentuk fisik bangunan rumah betang panjang hampir seluruhnya sama, yakni berciri panjang dan tinggi.
Rumah betang panjang merupakan rumah dengan rentetan bilik yang sambung menyambung menjadi satu kesatuan. Secara umum, banyaknya bilik yang ada di rumah betang tergantung seberapa banyak keluarga yang tinggal di situ. Ketinggian tiang-tiang penyangga (pilar) dari tanah ke lantai bangunan sekitar 6-8 meter. Hal ini bertujuan untuk mencegah gangguan dari binatang-binatang buas dan dari serangan musuh.[i] Selain itu pada masa lalu, sebagian besar masyarakat Dayak membangun rumah betang tidak terlalu jauh dari pinggiran sungai. Dengan bentuk bangunan yang tinggi akan lebih aman bila suatu ketika air sungai meluap dan banjir melanda.
Bagian berikutnya yang menjadi ciri fisik dari rumah betang panjang adalah ada dua ruangan di dalam rumah betang yang masing-masing bagian memiliki fungsi tersendiri, yakni serambi di bagian luar dan bilik di bagian dalam. Bilik merupakan sebuah ruangan tempat tinggal keluarga yang dibatasi oleh sekat-sekat yang bisa dibuka pasang. Satu kepala keluarga menempati satu bilik. Luas dari tiap-tiap bilik sangat bervariasi untuk tiap-tiap daerah. Biasanya, sebelum proses pembangunan, ada kesepakatan dari seluruh warga berkaitan dengan luas untuk tiap-tiap bilik. Di dalam bilik itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian kecil. Satu ruangan kecil sebagai kamar tempat tidur, ada satu ruangan untuk keluarga berkumpul (sejenis ruang keluarga) dan ada dapur di bagian belakang.[ii] Bila ada perayaan besar seperti Gawai, upacara kematian atau perkawinan, sekat-sekat yang ada di dalam tiap-tiap bilik itu akan dibuka sehingga akan menjadi satu ruangan yang luas yang bisa menampung seluruh tamu yang datang.[iii]
Kemudian, bagian lain yang ada di rumah betang panjang adalah serambi. Serambi merupakan satu ruangan yang luas tanpa sekat. Dari ujung ke ujung hanya ada satu hamparan ruangan terbuka. Fungsi dari serambi ini adalah sebagai tempat untuk pertemuan adat, bekerja, bertukar pikiran, belajar aneka keterampilan, ibadat-ibadat, dan lain-lain. Karena serambi adalah ruangan terbuka, maka setiap orang bisa saling berjumpa dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Apa bila ada perayaan-perayaan besar, serambi berfungsi sebagai pusat dari perayaan tersebut.[iv]
Rumah betang panjang adalah rumah dengan model satu atap dengan satu pintu masuk dan keluar. Oleh karena itu. Meskipun di dalam rumah betang panjang ada banyak bilik, namun hanya ada satu tangga untuk bisa keluar dari rumah menuju ke tanah. Inilah yang menjadi kekhasan dari rumah ini. Perlu dipahami bahwa satu pintu dengan satu tangga ini dibuat bukan tanpa makna apa pun. Tangga untuk keluar masuk rumah betang pun bukan seperti tangga biasa pada umumnya. Bentuk tangga selalu dibuat menyerupai bentuk tubuh manusia. Ada bagian tangan dan kepala di bagian atas tangga tersebut. Hal ini selain memiliki makna seni, juga memiliki makna religius. Dalam sistem kepercayaan tradisional masyarakat suku Dayak, satu tangga itu menyimbolkan bagaimana perjalanan jiwa manusia setelah mati akan berjalan naik menuju kembali kepada sang pencipta (Penompa). Sementara satu pintu menyimbolkan hanya ada satu yang menciptakan semua yang ada di dunia ini, dia itulah yang memberi, menjaga, dan melindungi. Dia itulah yang disebut sebagai Penompa (pencipta/pembentuk).[i]
Rumah Betang Panjang Sebagai Tempat Hunian
Sebelum mengenal sistem perumahan tunggal, masyarakat suku Dayak pada masa lalu hidup bersama di dalam satu kelompok masyarakat dengan satu rumah hunian bersama, yakni rumah betang panjang.[ii] Masyarakat Dayak pada saat itu masih memiliki naluri untuk selalu hidup bersama secara berdampingan dengan warga masyarakat lainnya. Mereka senang akan hidup yang damai dan harmonis dalam sebuah komunitas rumah betang panjang sehingga berusaha terus bertahan dengan rumah panjang mereka. Harapan ini di dukung oleh kesadaran setiap individu untuk menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan bersama. Kesadar ini dilandasi oleh alam pikiran religio-magis, yang menganggap bahwa setiap warga mempunyai nilai dan kedudukan serta hak hidup yang sama dalam lingkungan masyarakatnya.[i]
Sebagai sebuah rumah hunian, rumah betang panjang mempunyai peranan sebagai pemersatu untuk menjaga ikatan persaudaraan dan juga menjadi simbol identitas diri suku tersebut. Di dalam rumah betang panjang itu bila ada kegiatan, maka kegiatan itu akan dilakukan secara bersama-sama. Semangat gotong royong dan persatuan masih sangat terasa kental di dalamnya. Sebagai sebuah identitas diri, keberadaan rumah betang panjang menjadi simbol eksistensi sebuah kelompok masyarakat.[i] Sebab, di dalam rumah betang panjang itu ada sebuah struktur masyarakat seperti layaknya sebuah sistem kemasyarakatan pada umumnya. Ada perangkat-perangkat organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing. Dan, perlu diketahui bahwa meskipun rumah betang itu memiliki bentuk yang kurang lebih sama, namun tata kelola sistem kemasyarakatan tetap berdiri sendiri (otonom) sesuai dengan wilayah di mana rumah betang itu didirikan.
Kehidupan di dalam rumah betang panjang selalu didasarkan pada rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Pola pemukiman rumah betang panjang erat hubungannya dengan sumber-sumber makanan yang disediakan oleh alam sekitarnya, seperti lahan untuk berladang, sungai yang banyak ikan dan hutan-hutan yang dihuni binatang buruan.[ii] Tidak ada keluarga yang terlalu menonjol di dalam hal kekayaan. Apa bila ada memiliki kelebihan, maka mereka akan membagikan kepada yang kekurangan. Begitu juga apabila ada orang atau keluarga yang mendapatkan binatang buruan maka, mereka akan membagikan hasil buruan itu satu dengan yang lain.[iii]
Apabila ada waktu senggang di siang hari, umumnya ibu-ibu atau wanita akan mengerjakan kerajinan tangan seperti menenun atau menjahit sambil berbagi cerita satu dengan yang lain. Sementara itu bapak-bapak atau para lelaki, mereka biasanya mengerjakan alat-alat kerja seperti parang, jarai, membuat jala atau bubu.[iv] Hal ini biasa dilakukan sebagai bentuk keakraban dan persaudaraan sebagai satu keluarga yang berhimpun dan berlindung di bawah atap yang sama yaitu di rumah betang panjang.
Namun, di sisi yang lain meski hidup di dalam rumah betang di dasarkan pada nilai-nilai kebersamaan, rumah betang panjang juga terbuka untuk tiap-tiap keluarga menjaga ruang privasi mereka masing-masing. Kenyataan ini tergambar jelas dari aturan yang diberlakukan untuk tiap penghuni bilik, yakni tidak sembarang orang boleh keluar masuk bilik orang lain tanpa izin. Kecuali apabila ada perayaan tertentu, sekat bilik akan dibuka, dan orang boleh untuk berpindah dari bilik yang satu ke bilik yang lain dengan lebih leluasa.[i]
Rumah Betang Panjang Sebagai Pusat Organisasi Sosial
Masyarakat suku Dayak memang tidak mengenal sistem masyarakat bertingkat (kasta) seperti yang dikenal oleh beberapa suku bangsa seperti di Bali atau di Jawa. Namun sebagai sebuah kelompok masyarakat, struktur-struktur organisasi tetaplah ada. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata kelola hidup bersama di rumah betang panjang, agar tercipta ketertiban dan kenyamanan di antara keluarga-keluarga yang tinggal di dalamnya. Ada struktur masyarakat, sistem politik dan sistem hukum adat yang tersusun rapi dan khas.[ii]
Dalam menentukan dan memilih struktur kepengurusan masyarakat yang ada di rumah betang panjang, biasanya diadakan musyawarah bersama seluruh penghuni rumah betang yang telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Dari musyawarah tersebut kemudian ditentukanlah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk kemudian dipilih menjadi ketua suku yang akan memimpin seluruh keluarga yang ada di rumah betang panjang itu. Selain memilih ketua suku, musyawarah ini juga memilih struktur pengurus masyarakat lainnya seperti pemimpin upacara ritual religius dan ketua adat yang menjadi penegak hukum adat; serta mengawasi dan memutuskan perkara-perkara adat.[iii]
Rumah Betang Panjang sebagai Sekolah non-formal bagi kebudayaan, Seni dan Tradisi
Pada zaman dahulu, ketika sekolah-sekolah formal masih sangat langka dan sulit untuk dijangkau. Kehadiran rumah betang bisa dibilang menjadi pilar utama bagi orang-orang Dayak untuk belajar berbagai macam pengetahuan, terlebih terkait dengan nilai-nilai kebudayaan, bentuk-bentuk kerajinan tangan dan kesenian, serta kearifan lokal lainnya.[iv] Mereka belajar sebagaimana seharusnya bekerja, namun sekaligus juga mencintai dan menghargai alam sebagai ibu yang memberikan kehidupan kepada mereka. Belajar menggunakan kearifan lokal untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan. Singkat kata, rumah betang panjang menjadi sekolah non-formal bagi warganya.[v]
Kenyataan bahwa rumah betang panjang menjadi sekolah non-formal ini bisa dilihat dari kebiasaan warga yang ada di rumah betang ketika waktu sedang senggang. Pada siang hari, sebagian dari mereka ada yang mengerjakan kerajinan tangan, seperti anyaman dan menenun. Ada juga yang mengerjakan alat-alat pertanian. Ada juga yang bernyanyi dan bermain musik. Sementara itu, ketika malam hari, anak-anak mendengarkan kisah-kisah dongeng rakyat dari para nenek, sementara orang-orang tua yang laki-laki duduk bersama di serambi, saling bertukar pikiran sambil meminum tuak.[vi]
Kegiatan-kegiatan semacam ini merupakan salah satu model pendidikan non formal yang diwariskan oleh para orang tua kepada generasi sesudahnya dan hal itu hanya bisa di dapat apabila mereka masih tinggal di rumah betang panjang. Secara mandiri dan tanpa teori mereka belajar membuat kerajinan, kesenian dan memelihara tradisi serta nilai-nilai kebudayaan yang selama ini telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Makna Religius dari Rumah Betang Panjang
Orang Dayak sering dikaitkan orang yang lekat dengan unsur supranatural atau manusia magic. Perspektif ini muncul ketika orang di luar suku Dayak membaca atau mendengar kisah-kisah tentang orang Dayak yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya tanpa menyentuh dan tanpa kelihatan, punya ilmu kebal, dan lain-lain. Intinya orang Dayak dianggap sebagai orang yang sakti.[i] Sebetulnya perspektif semacam itu tidak berimbang dan cenderung menciptakan fobia bagi orang-orang yang tidak mengenal orang Dayak.
Religiusitas orang Dayak bukan melulu berkaitan dengan praktek-praktek supranatural semacam itu. Dalam peribadatan ritual tradisional orang Dayak, ada nilai-nilai moral yang sangat ditekankan. Sebagai contoh, sebelum orang Dayak membangun rumah betang panjang, mereka harus terlebih dahulu mengadakan sebuah ritual tradisional, memohon izin kepada Penompa agar memberkati dan melindungi tanah yang akan digunakan, bagi rumah yang akan dibangun dan bagi orang-orang yang akan berdiam di dalamnya. Contoh lain adalah ketika hendak membuka hutan untuk dijadikan ladang, ada ritual-ritual yang dilakukan sebagai cara mereka memberikan penghormatan kepada alam dan mohon restu kepada Penompa. Intinya religiusitas orang Dayak adalah religiusitas yang membatin. Sebab, baik manusia maupun alam adalah sama-sama berasal dari Penompa.[ii]
Sekarang, apabila berbicara tentang aspek religius dari rumah betang panjang, kita bisa mendalami itu dari bentuk fisik dari rumah tersebut. Secara umum, rumah betang panjang selalu memiliki ciri yang khas, yakni tinggi, besar, panjang, memiliki satu pintu dan memiliki satu tangga sebagai jalur lintasan orang masuk dan keluar. Mengapa ciri fisik semacam itu hanya dimiliki oleh rumah betang panjang? Berdasarkan tinjauan antropologis rumah betang panjang merupakan rumah sekaligus ‘kampung’ bagi setiap sub suku Dayak. Di dalamnya mereka berlindung, bernaung dan hidup. Selain itu, di dalam rumah betang panjang itu juga penerusan tradisi, seni budaya, adat-istiadat, ritual keagamaan, dan lain-lain di selenggarakan[iii]
Sementara berdasarkan tinjauan religiusnya, rumah betang panjang merupakan sebuah gambaran kehidupan manusia setelah kematian. Bentuk rumah yang menjulang tinggi melukiskan bagaimana ketika manusia itu mati, roh akan meninggalkan badan dan berjalan naik menuju kehidupan yang baru bersama dengan Penompa. Perjalanan naik menuju ke kehidupan itu dilukiskan dengan tangga rumah betang panjang yang bentuknya menyerupai manusia. Sedangkan, satu pintu sebagai jalur keluar masuk itu mempunyai makna, hanya manusia yang mampu hidup selaras dan bersahabat dengan alam dan sesama yang boleh berjalan melewati pintu itu dan masuk ke dalam kehidupan abadi bersama dengan Penompa.
Estetika Rumah betang
Rumah betang memiliki unsur estetikanya, yaitu dari bentuk fisik yang memanjang dan memiliki pintu keluar di tengah, hal ini sama dengan estetik dalam keseimbangan formal, yaitu keseimbangan pada dua pihak berlawanan dari satu poros dan memiliki sifat yang statis.[iv] Estetika lain juga terdapat dalam ukiran-ukiran pahat motif Dayak yang terdapat di dalam tiang rumh betang dan di dinding pada sebuah rumah, hal ini sama dengan stilisasi dalam estetika.[v] Masih banyak estetika yang terdapat dalam rumah betang yang tidak ditampilkan, karena bagi orang Dayak memang ada hal yang tidak sembarangan orang bisa melihatnya, karena bisa mengakibatkan sakit atau sebagainya.
Penutup
Rumah betang menjadi bukti adanya sejarah bagi keberlangsungan hidup orang Dayak pada zaman dulu. Dimana rumah betang panjang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan rasa solidaritas dan kekeluargaan serta semangatgotong royong di antara suku Dayak. Satu motto yang melekat bagi orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan Barat khususnya, yaitu: “Adil Ka` Talino Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ke` Jubata” artinya, adil terhadap sesama manusia, memandang ke surga dan hidup berserah kepada yang Maha kuasa.[i]
Kebudayaan yang seiring dengan waktu mulai tergerus oleh modernisasi, keberadaan rumah betang yang dianggap sudah tidak cocok lagi bagi zaman ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Namun, kita perlu ingat bahwa saat ini “ada” karena ada sejarah, oleh sebab itu, kebudayaan akan rumah betang panjang yang baik, yang pernah dihidupi oleh nenek moyang kita harus kita tingkatkan. Dengan demikian, rasa kecintaan akan kebudayaan asli kita akan semakin menggelora dan semakin lestari di bumi Indonesia kita ini.
[1] Paulus Florus, dkk., Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 204.
[1] Paulus Florus, dkk., Kebudayaan Dayak: Aktualisasi …, hlm. 205.
[1] Paulus Florus dkk., Kebudayaan Dayak: Aktualisasi …, hlm. 205.
[1] Michael R. Dove, Sistem Perladangan Di Indonesia (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1998), hlm. 56.
[1] Soenaptpo, dkk. Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 169.
[1] Soenaptpo, dkk. Arsitektur Tradisional…, hlm. 171.
[1] Herman Josef van Hulten, Hidupku Di Antara Suku Dayak (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 159.
[1] Soenaptpo, dkk. Arsitektur Tradisional…, hlm. 173.
[1] Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 98.
[1] Y. C. Thambun Anyang, Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 78.
[1] Paulus Florus dkk., Kebudayaan Dayak: Aktualisasi …, hlm. 206.
[1]. John Bamba, Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat (Pontianak: Institut Dayakologi, 2008), hlm. 120.
[1] Paulus Florus dkk., Kebudayaan Dayak: Aktualisasi …, hlm. 206
[1]Herman Josef van Hulten, Hidupuku Di Antara …, hlm. 163.
[1] Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun …, hlm. 106.
[1] John Bamba et al., Mozaik Dayak: Keberagaman …, hlm. 124.
[1] Fridolin Ukur, Tantang-Djawab Suku Dajak (Djakarta: BPK Gunung Mulia, 1971), hlm. 57.
[1] Fridolin Ukur, Tantang-Djawab…, hlm. 58.
[1] Herman Josef Van Hulten, Hidupku Di Antara …, hlm. 163.
[1] Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun …, hlm. 110.
[1] Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun …, hlm. 112.
[1] Herman Josef van Hulten, Hidupku Di Antara …, hlm. 165.
[1] Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun …, hlm. 112.
[1] Soenaptpo et al., Arsitektur Tradisional …, hlm. 175.
[1] Lingga Agung, Pengantar dan Konsep Estetika (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 13.
[1] Lingga Agung, pengantar dan Konsep…, hlm. 7.
[1] Nico Andasputra dan Vincentius Julipin, Mencermati Dayak Kanayatn (Pontianak: Institute of Dayakology Researc and Development, 1997), hlm. 51.
Daftar Pustaka
Agung, Lingga. Pengantar Sejarah dan Konsep Estetika. Yogyakarta. Kanisius. 2017.
Anyang, Thambun Y. C. Kebudayaan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi. Jakarta: Grasindo. 1998.
Bamba, John (ed). Mozaik Dayak (Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat). Pontianak: Institut Dayakologi. 2008.
Dove, Michael R. Sistem Perladangan di Indonesia. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 1988.
Florus, Paulus dkk. Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi. Jakarta: Grasindo. 1994.
Julipin, Vincentius and Nico Andasputra. Mencermati Dayak Kanayatn. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development. 1997.
Hulten, Herman Josef. Hidupku di Antara Suku Dayak. Jakarta: Grasindo. 1992.
Ukur, Fridolin. Tantang-Djawab Suku Dajak. Djakarta: BPK Gunung Mulia. 1971.
Wuryanto, Herry Soenaptpo dkk. Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986.